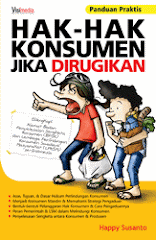Oleh Happy Susanto
Dimuat dalam Harian Suara Pembaruan, 27 Februari 2004.
Pada tanggal 23-26 Februari 2004 ini, diadakan International Conference for Islamic Scholars yang bertajuk "Upholding Islam as Rahmatan Lil 'alamin". Acara ini diadakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Kementerian Luar Negeri (Menlu) RI. Hasil yang ingin dicapai dari cara ini adalah (1) pernyataan-pernyataan yang merefleksikan pandangan komprehensif bagaimana umat ini merespons berbagai tantangan di masa depan, (2) rencana kerja untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan Islam sebagai rahmatan lil a'lamin. Konferensi ini juga ingin mendialogkan Islam dengan agama lain, komunitas lain, dan terutamanya dengan Barat. Lebih jauh lagi, konferensi ini juga ingin mengembangkan peran civil society dalam pandangan Islam.
Acara ini patut diapresiasi, terlepas apakah ada motif politik atau tidak di balik perhelatan ini. Yang jelas, kita sangat membutuhkan wajah Islam yang damai, toleran, dan penuh mengajarkan kemanusiaan. Prof Dr Mohammad Sayed Tantawi pada pidato pembukaan konferensi itu menegaskan bahwa bimbingan dan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW menjadi obat dan rahmat bagi sekalian alam. Islam adalah agama kemanusiaan yang bukan hanya khusus bagi umat Islam karena agama ini memang dibawa oleh semua nabi. Menarik sekali pernyataan yang dikemukakan Tantawi, Sheikh Al-Azhar yang sangat dikenal moderat ini.
Hassan Hanafi (2001:131-137), intelektual progresif asal Mesir juga menegaskan bahwa Islam adalah agama perdamaian yang universal. Menurutnya, secara literal semua nabi terdahulu adalah muslim karena mereka menundukkan kehendaknya di bawah kehendak suci Tuhan. Wahyu yang mereka terima sebenarnya bertalian dalam satu mata rantai yang kemudian dipadukan dan disempurnakan dalam Islam. Jadi, Islam adalah agama yang dibawa setiap nabi untuk semua individu, semua bangsa, dan seluruh umat manusia. Di sinilah kode etik universal perlu diangkat sebagai jaminan atas cita-cita perdamaian dalam Islam, yaitu kesamaan esensi misi mereka dalam upaya menciptakan kemanusiaan dan keadilan di muka bumi.
Kekerasan
Sekarang ini umat Islam selalu dipojokkan dan seakan menjadi "pihak terdakwa" dari berbagai kasus tindak kekerasan, seperti kasus 11 September dan bom Bali. Tentu, pencitraan negatif ini membuat umat Islam tidak tenang dan merasa perlu untuk mengklarifikasi akan hal itu. Secara objektif, tidak bisa kemudian umat Islam secara keseluruhan dianggap sebagai penganut agama yang dikata menyesatkan. Seperti yang kita yakini, Islam adalah agama keselamatan (salamah). Hanya saja, perilaku oknum tertentu yang memakai jubah agama menyebabkan distorsi pemahaman mengenai Islam.
Kekerasan atas nama agama memiliki muatan yang sangat kompleks. Paling tidak, ada dua sisi yang menyebabkan Islam kemudian dipandang sebagai agama yang "bermasalah" gara-gara kekerasan atas nama agama itu. Pertama, bisa dilihat secara internal. Boleh jadi, kekerasan itu memang benar-benar dilakukan oleh sebuah organisasi atau beberapa oknum yang mengaku sebagai penganut sebuah agama. Mereka melakukan itu disebabkan oleh sempitnya pemahamannya atas agama, dibarengi oleh sikap emosi yang tak tertahankan. Pemaknaan tekstual atas konsep jihad dan kafir menjadi penyebab aksi kekerasan yang mereka lakukan.
Kedua, secara eksternal. Pencitraan Islam yang dilakukan media asing menimbulkan bias tersendiri. Dalam pandangan dunia internasional, Islam seakan-akan dianggap sebagai "agama teroris". Di tengah suasana menegangkan, terkadang media bisa menjadi pemicu yang menambah rumit keadaan. Seharusnya, media perlu bersikap objektif dan membeberkan berita mengenai Islam secara faktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Media asing (Barat) memiliki banyak kelemahan dalam mencitrakan Islam di saat menghubungkannya dengan peristiwa pengeboman dan aksi kekerasan.
Pertemuan yang diadakan PBNU dan Deplu itu memiliki relevansi yang sangat signifikan untuk memberikan citra baru (yang sesungguhnya) atas Islam, yaitu Islam sebagai rahmatan lil 'Alamin (rahmat bagi seluruh sekalian alam). Selain itu, perlu juga perbincangan mengenai bagaimana Islam itu menyikapi tantangan dan perubahan yang ada. Islam adalah agama yang dihadirkan ke muka bumi untuk memberikan rahmat dan perdamaian bagi setiap manusia, tanpa membedakan suku, ras, dan agamanya. Substansi yang ingin diperjuangkan Islam adalah bagaimana kemanusiaan dan keadilan itu benar-benar telah ditegakkan di bumi ini.
Moderatisme
Upaya strategis untuk membumikan risalah perdamaian dalam Islam adalah dengan membangun sikap moderatisme dalam beragama. Sikap ini perlu disertai dengan upaya pengembangan peran profetis agama yang banyak mengajarkan kemanusiaan. Pesan tersebut bisa kita rujuk pada al-Qur'an yang menyatakan bahwa "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah" (Ali Imron, 3 : 110). Ada tiga makna yang terkandung dlaam ayat ini, yaitu "ma- syarakat utama" (khairu ummah), "kesadaran sejarah" (ukhrijat linnas), "liberasi" (amr ma'ruf), "emansipasi" (nahy munkar), dan "transendensi" (al-iman billah).
Konsep "amar ma'ruf" (menyuruh pada kebaikan) dan "nahy munkar" (mencegah kemungkaran) banyak ditafsirkan sebagai bentuk dakwah yang dilakukan secara formal dan terkadang sering menggunakan cara kekerasan. Padahal, ada makna lain di balik itu, yaitu memberikan pemahaman yang baik pada umat mengenai ajaran-ajaran kebaikan agama dengan memberikan ruang kebebasan pada manusia itu sendiri. Substansinya bahwa Islam mengajarkan mengenai pesan-pesan ibadah, muamalah, dan syariah, yang kesemuanya itu diorientasikan untuk meraih makna hidup yang berlandaskan pada kemanusiaan. Dakwah yang banyak dilakukan selama ini hanya berorientasi pada pencapaian makna agama secara normatif. Seharusnya umat perlu juga diajak berpikir kritis terhadap berbagai fenomena yang ada dalam penampakan realitas keseharian mereka.
Pola pemikiran Islam yang profetis itu diaplikasikan dalam sebuah sikap moderatisme dalam beragama. Sikap ini sangat ditekankan dalam Islam. Sikap moderatisme umat Islam (ummatan wasthan) akan melahirkan kedewasaan dalam beragama sehingga akan sangat objektif dalam menyikapi segala persoalan yang ada dalam realitas sosial. Fenomena radikalisme agama disebabkan karena emosi beberapa pihak umat Islam yang tidak bisa ditahan. Belum lagi, hal itu diperkuat oleh pemahaman keagamaan yang sangat sempit. Misalkan, konsep mengenai jihad. Bagi mereka, jihad melawan kemungkaran dan "musuh-musuh" Allah adalah kemestian agama dan menjadi ukuran keberislaman seseorang. Maka, kekerasanlah yang sangat mungkin mereka lakukan. Tentu, ini sangat berbahaya.
Moderatisme beragama akan mengerem sejauh mana umat Islam ini harus pintar dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada. Sikap moderat juga akan menghilangkan kecurigaan dalam memandang umat di luar Islam. Umat beragama yang lain adalah saudara sendiri dan mereka perlu diperlakukan secara damai dan toleran. Polarisasi antara Islam dan "yang lain" (the others), begitu pula perbedaan antar madzhab pemikiran dalam Islam juga perlu dicairkan. Pandangan inklusif dan pluralis harus terus dikembangkan dan disosialisasikan pada masyarakat Islam secara keseluruhan.
Islam adalah agama yang damai dan penuh mengajarkan kemanusiaan. Perdamaian adalah jiwa Islam yang telah mengakar sejak agama ini diturunkan ke muka bumi. Islam bukanlah ajaran mengenai kekerasan. Umat Islam perlu meluruskan makna Islam ini dengan memberikan pemahaman baru terhadapnya. Disertai sikap moderatisme dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam konteks masa sekarang ini. Wallahu A'lam.
Sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2004/02/27/index.html
Daftar Tulisan
Tuesday, August 14, 2007
Radikalisme dan Dialog Antar Agama
Oleh Happy Susanto
Dimuat dalam Harian Suara Pembaruan, 10 Desember 2004.
Di Yogyakarta, pada 6-7 Desember 2004 lalu, diselenggarakan "Dialog Internasional tentang Kerja Sama Antar-Agama" yang merupakan kerja sama antara Departemen Luar Negeri RI, Departemen Luar Negeri Australia, dan PP Muhammadiyah. Tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan kesepahaman antar- umat beragama agar mampu mencegah radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama.
Hadir dalam acara ini sekitar 150 tokoh agama dan aliran kepercayaan dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik, seperti ASEAN, Australia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Selandia Baru.
Motif acara tersebut hampir mirip dengan International Conference for Islamic Scholars dengan tajuk "Upholding Islam as Rahmatan Lil 'alamin" pada 23-26 Februari 2004 lalu yang diadakan oleh kerja sama PBNU dan Deplu RI. Hanya saja, bedanya acara kali lebih bersifat luas karena mengundang seluruh tokoh antar-agama dengan cakupan regional.
Acara-acara semacam ini perlu dikembangkan. Persoalan terorisme dan radikalisme agama menjadi problem besar dunia. Dengan diadakannya acara ini, secara khusus sebenarnya pihak Australia berharap bahwa akan ada jaminan keamanan yang diberikan oleh Indonesia, dan komunitas-komunitas agama di negara ini mampu menciptakan kehidupan yang damai dan beradab.
Harapan yang bisa diraih bagi pihak Indonesia adalah tentang jaminan investasi dan hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Australia yang beberapa saat lalu sempat merenggang karena terjadinya aksi pengeboman di sejumlah tempat. Pihak Muhammadiyah sebagai ormas Islam moderat ingin menunjukkan komitmennya bahwa Islam di Indonesia perlu dihadirkan sebagai agama yang ramah, damai, dan toleran. Islam bukanlah agama kekerasan.
Acara yang digelar selama dua hari ini, di samping membicarakan tentang ancaman terorisme global juga membicarakan tentang bagaimana membangun tatanan dunia yang adil dan beradab. Jalinan terorisme dan ketidakadilan global terlihat begitu kompleks sehingga memerlukan pemecahan yang mampu membacanya secara jernih dan terbuka.
Terorisme Global
Dunia internasional kini sedang dilanda sebuah masalah besar, yaitu terorisme global dan ancaman terhadap perdamaian dunia. Semenjak terjadinya serangan terhadap menara kembar WTC pada 11 September 2001, dunia internasional dikejutkan oleh sebuah ancaman terorisme global. Konon aksi ini didalangi oleh kelompok terorisme internasional bernama al-Qaeda, sebuah jaringan yang dipimpin oleh Osama bin Laden.
Seperti pernah santer dibicarakan bahwa aksi terorisme ini sengaja dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuatan Amerika Serikat (AS) yang kebijakan-kebijakan luar negerinya dianggap banyak menyebabkan penderitaan di berbagai negara Islam di Timur Tengah, seperti Palestina, Afghanistan, Irak, dan sebagainya. Tindakan terorisme dilakukan sebagai bentuk pelajaran yang harus diterima pihak AS karena ulah mereka selama ini.
Kejadian semacam itu juga menimpa beberapa negara di dunia ini. Makanya, disebut sebagai terorisme global. Di Indonesia, pernah terjadi peledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002, peledakan bom di Hotel Marriott di Jakarta, dan beberapa bulan lalu terjadi pula peledakan bom di depan Kedubes Australia.
Beberapa tindakan terorisme tersebut menunjukkan bahwa ancaman terorisme global tidak dapat dianggap sepele. Banyak orang merasa khawatir akan terjadi lagi aksi-aksi semacam itu di kemudian hari. Rasa aman dan keselamatan menjadi sebuah harga mahal yang harus dibayar.
Memang, kita tidak bisa menampik bahwa muncul dan berkembangnya terorisme tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketidakadilan global. Pihak yang melakukan aksi-aksi terorisme merasa tidak mendapatkan keadilan yang diberikan dunia internasional, sehingga mereka menjawabnya dengan kekerasan.
Akan tetapi, jawaban kekerasan ini pun tidak dapat dibenarkan. Tindakan antikemanusiaan semacam ini mengakibatkan timbulnya banyak korban jiwa yang melayang dan justru kian memperparah keadaan. Ada pepatah mengatakan bahwa kekerasan akan dibalas dengan kekerasan, dan kekerasan menjadi "lingkaran setan".
Buktinya, aksi terorisme itu berbuntut makin memarahkan pihak AS dengan melancarkan serangan balasan terhadap Afghanistan yang dicurigai menyimpan Osama, sehingga menimbulkan banyak korban di rakyat Afghanistan itu sendiri.
Dalam menyikapi kasus terorisme, langkah yang tepat adalah dengan jalan perdamaian. Inilah salah satu gagasan yang diusung melalui kegiatan dialog internasional tersebut. Jalan damai tidaklah menyurutkan usaha untuk selalu mengatasi persoalan terorisme. Bila kekerasan sebagai jawaban maka akan banyak korban jiwa tak berdosa yang akan timbul. Kalau demikian yang terjadi, gerakan antiterorisme justru melanggar hak asasi manusia.
Pertarungan Wacana
Ada yang menarik tatkala Menlu Australia Alexander Downer memberikan beberapa butir pemikirannya perihal radikalisme dan terorisme dengan atas nama agama. Menurut Downer, memerangi terorisme menuntut adanya upaya untuk memenangi pertarungan ide (wacana) sebagai bentuk penyelesaian secara damai.
Artinya, perjuangan melawan terorisme tidak lepas dari keberhasilan memberdayakan mayoritas umat beragama yang moderat di masyarakat dan kerelaan mereka untuk melakukan kerja sama guna menolak ajaran kebencian dan kekerasan yang menyimpang. Melalui acara tersebut diharapkan para tokoh masing-masing agama mampu melakukan wacana saling pengertian dan kerukunan antarkomunitas.
Gagasan yang ditawarkan Downer itu sungguh sangat strategis dan menghindari cara-cara penuh kekerasan dalam menangani kasus terorisme. Pertarungan wacana yang dimaksud adalah bagaimana seluruh agama mampu menghadirkan pembacaan yang moderat dalam menyikapi keberagamaan dirinya terhadap pihak atau komunitas di luar dirinya.
Downer bermaksud ingin memperhadapkan wacana yang diusung kalangan fundamentalis dengan wacana yang liberal dan humanis dari kalangan moderat. Saya pikir strategi ini perlu diapresiasi. Membangun sikap dan pemahaman agama yang moderat adalah bagian dari upaya untuk menghadirkan agama yang antikekerasan.
Dengan sikap semacam ini diharapkan hubungan antara "diri seseorang" (self) dengan "orang lain "the other" dapat terjalin secara harmonis dan toleran. Dalam hidup ini sering terjadi kecurigaan antara seseorang dengan orang lain, antara satu pihak dengan pihak lain, apalagi kecurigaan tersebut berhubungan dengan problem identitas agama.
Ambil contoh, misalkan hubungan antara seorang Muslim dan seorang Kristiani yang penuh diliputi rasa kecurigaan dan masing-masing menganggap bahwa agamanya paling benar. Tentunya, hubungan semacam ini sangat berbahaya karena mengundang konflik yang sungguh serius.
Hal itu terjadi disebabkan karena pemahaman keagamaan mereka yang sama-sama sempit, tidak mau mencoba memahami ajaran agamanya dan keberadaannya masing-masing. Sikap yang seharusnya dibangun adalah dengan sikap moderat, yaitu mau mencoba untuk memahami dan membangun saling pengertian, apalagi bersedia menjalin kerja sama dalam urusan-urusan moral dan kemanusiaan.
Ketegangan antara "self" dan "the other" ini perlu dilebur. Bila hubungan ini masih saja terjadi dan menguat dalam skala besar maka potensi konflik komunal tidak akan tertampik. Untuk itulah, para tokoh agama-agama harus membangun saling pengertian bahwa dunia ini membutuhkan perdamaian antar-umat beragama.
Demikian halnya, perlu dibangun kesadaran bahwa kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyikapi berbagai macam persoalan, karena memang agama sama sekali tidak mengajarkan kekerasan.
Untuk menumbuhkan saling pengertian semacam ini maka perlu dibangun "dialog antaragama" dalam membahas segala persoalan yang sangat membutuhkan perhatian kaum agamawan. Radikalisme dan terorisme adalah salah satu persoalan besar yang perlu dibicarakan dalam dialog antar-agama ini.
Selama ini model dialog antar-agama sering dilakukan dalam upaya mencari "common platform" (titik temu) pemahaman bersama tentang ajaran agamanya masing-masing. Akan tetapi, bentuk dialog internasional yang diadakan di Yogya ini modelnya dibangun secara lebih luas. Seluruh tokoh agama diundang untuk berbicara tidak lagi hanya soal ajaran agamanya saja, tapi sudah beranjak pada bagaimana menyikapi kasus terorisme yang kian melanda dunia dan mengancam perdamaian dunia.
Terorisme dan radikalisme dijadikan sebagai "common enemy" (musuh bersama) yang harus terus diberantas oleh seluruh pihak di masing-masing agama. Sikap kekerasan tumbuh dan sering terjadi di setiap agama. Gejala fundametalisme kian mewabah pada setiap agama dan justru menimbulkan citra yang buruk karena aksi-aksi radikalisme dan terorisme sering mewarnai kehidupan (keberagamaan) mereka. Untuk itulah, dialog antar-agama ini adalah momentum besar untuk menghadapi persoalan sangat serius ini.
Kita perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat-agama bahwa terorisme sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Emosi dan kekerasan bukanlah jawaban dalam menyikapi segala persoalan. Agama hanya mengajarkan bahwa dalam menghadapi suatu persoalan serumit apa pun maka kita harus menggunakan akal dan kejernihan dalam berpikir.
Sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2004/12/10/content.html
Islam Humanis
Oleh Happy Susanto
Dimuat dalam Harian Sinar Harapan, 15 Oktober 2003.
Ide ”Islam Humanis” menjadi penting untuk didiskusikan kembali karena ”tamparan” hebat modernitas yang menggerus kepekaan kemanusiaan global. Dan juga disebabkan karena peran agama yang secara negatif telah disalahgunakan oleh penganutnya. Fenomena pengeboman dan aksi terorisme yang kian marak terjadi menambah rentetan derita kemanusiaan.
Wacana mengenai Islam dan humanisme menjadi penting untuk diperbincangkan kembali. Apakah Islam cenderung berlawanan dengan ajaran kemanusiaan? Bagaimana ada kemungkinan untuk membangun ruang dialog dalam upaya menghubungkan Islam dengan humanisme (ajaran kemanusiaan)? Upaya ini bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam agar lebih berwajah humanis dan berorientasi pada pemenuhan cita-cita kemanusiaan.
Humanisme Barat
Gerakan Renaisans (Pencerahan) yang muncul Pasca-Abad Pertengahan memberikan angin segar perubahan menuju pencerahan intelektualisme dan rasionalisme. Gereja dan agama yang telah menutup ruang kebebasan bagi manusia yang kemudian diprotes oleh Reformasi Protestan, melapangkan jalan sekularisasi antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Renaisans adalah era ”kebangkitan kembali” untuk menggali kebudayaan-kebudayaan Yunani dan Romawi, yang telah berabad-abad lamanya dikubur oleh masyarakat abad pertengahan di bawah kekuasaan gereja.
Pada masa inilah gerakan humanisme muncul. Warisan Yunani-Romawi yang dibangkitkan kembali adalah penghargaan atas dunia-sini, penghargaan atas martabat manusia, dan pengakuan atas kemampuan rasio. Gerakan humanisme mempercayai akan kemampuan manusia (sebagai ganti atas kemampuan adikodrati), hasrat intelektual, dan penghargaan atas disiplin intelektual. Pada masa abad pertengahan, segala hal pemikiran yang berbau rasio dan filosofis diharamkan, semua harus mengikuti doktrin agama (Kristiani).
Humanisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan pokok yang dimilikinya adalah untuk keselamatan dan kesempurnaan manusia (Ali Syari’ati,1989). Atau humanisme bisa juga diartikan sebagai paham pemikiran dan gerakan kultural yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai subyek yang bebas dan berdaulat dalam menentukan hidupnya (Sudarminta, 2001). Intinya, humanisme ingin meneguhkan kemampuan manusia secara bebas dan berdaulat untuk mengarungi hidupnya sendiri.
Dalam pandangan liberalisme Barat, tercapainya pengembangan potensi-potensi manusia bisa dilakukan dengan cara memberikan kebebasan pribadi dan kebebasan berpikir kepada manusia. Marxisme sebaliknya menyatakan bahwa kemanusiaan bisa ditegakkan apabila persamaan manusia yang tidak mengakui kebebasan-kebebasan tersebut, dan memasungnya ke dalam kepemimpinan diktator tunggal, yang dibantu oleh kelompok dan ideologi tunggal. Sebaliknya, eksistensialisme memberikan justifikasi filosofis bahwa manusia adalah makhluk yang berwujud dengan sendirinya di alam semesta. Yakni, makhluk yang dalam dirinya tidak terdapat bagian atau karakteristik tertentu yang datang dari Tuhan atau alam.
Humanisme yang terdapat pada ketiga aliran di atas berasal dari konsepsi Humanisme Yunani. Konsep ini berasal dari pertarungan antara langit dan bumi. Seluruh perbuatan dan kesadaran manusia dipimpin oleh kekuasaan yang zalim, yaitu para dewa sehingga manusia mencoba untuk membebaskan diri dari cengkeram kekuasaannya. Humanisme Yunani berusaha untuk mencapai jati diri manusia dengan segala kebenciannya kepada Tuhan dan pengingkaran atas kekuasaan-Nya. Ali Syari’ati memasukkan agama (termasuk Islam) sebagai salah satu madhab atau aliran humanisme.
John Avery, dalam dialognya dengan Hassan Askari yang terekam dalam buku Towards a Spiritual Humanism: A Muslim Humanist Dialogue (Meed: Seven Mirros,1991), mencatat bahwa kemunculan humanis agamis abad ke-20, seperti John Dewey, Roy Wood Sellars, dan sebagainya dari kubu Universitas Cambridge, menemukan unsur-unsur humanitarian dalam agama. Misalnya, ungkapan Yesus yang selalu mencintai manusia dengan doktrin kasih sayangnya, juga ajaran Islam yang menaruh perhatian terhadap aspek-aspek kemanusiaan. Kelompok humanis agamis berargumen bahwa agama dan kebudayaan manusia membantu atas kesadaran diri yang akan memeliharanya dari keterasingan hidup di dunia.Agama dan humanisme tidak selamanya berada pada ruang penuh pertentangan. Karena, ajaran agama yang dimaknai secara humanis dan rasional akan melapangkan citra positif bagi peran agama yang apresiatif dengan konteks kemanusiaan. Demikian halnya hubungan antara Islam dan humanisme. Ali Syari’ati memasukkan agama (termasuk Islam) sebagai salah satu madhab atau aliran humanisme.
Humanisme dalam Islam
Jika kita perhatikan sebenarnya Islam tidak bertentangan dengan humanisme. Tugas besar Islam, sejatinya adalah melakukan transformasi sosial dan budaya-budaya dengan nilai-nilai Islam. Kita mengenal trilogi ”iman-ilmu-amal” ; artinya iman berujung pada amal/aksi, atau tauhid itu harus diaktualisasikan dalam bentuk pembebasan manusia. Pusat keimanan Islam memang Tuhan, tetapi ujung aktualisasinya adalah manusia. Dalam penyataan Cak Nur (1995), pandangan hidup yang teosentris dapat dilihat dalam kegiatan keseharian yang antroposentris.
Dalam pandangan Kuntowijoyo (1991), Islam adalah sebuah humanisme, yaitu agama yang sangat mementingkan manusia sebagai tujuan sentral. Humanisme adalah nilai dasar Islam. Ia memberikan istilah dengan ”Humanisme Teosentris”, dengan pengertian ”Islam merupakan sebuah agama yang memusatkan dirinya pada keimanan Tuhan, tetapi yang mengarahkan perjuangannya untuk kemuliaan peradaban manusia”.
Islam sangat menjunjung tinggi rasionalisme. Untuk menghubungkan Islam dengan persoalan kemanusiaan dan humanisme maka teks keagamaan harus didekati secara rasional. Berbeda dengan Humanisme Teosentris, yang masih berangkat pada ajaran normatif agama --dengan pengandaian sudah final-- ”Humanisme Teistik”, sebagai istilah baru, memandang bahwa persoalannya terletak pada teks agama. Bagaimana sikap kita memperlakukan teks agar sesuai dengan konteks kekinian dan kemaslahatan (maslahah).
M. Abed Al-Jabiri (1991) menyodorkan dua model pembacaan terhadap teks keagamaan (tradisi) agar sesuai dengan konteks kekinian, yaitu ”Obyektivisme” (maudlu’iyyah) dan ”Rasionalitas” (ma’quliyah). Langkahnya, Pertama, bagaimana menjadikan tradisi lebih kontekstual dengan kekinian, tapi memisahkan terlebih dahulu dengan konteks yang ada agar didapati pemaknaan yang obyektif. Kedua, baru kemudian bagaimana memproyeksikan posisi obyektif itu dengan bagan rasionalitas yang relevan dengan masa kini.
Humanisme dalam Islam mengandung dua dimensi, yaitu ”rasionalitas” (rationality) dan ”pembebasan” (humanity). Dua dimensi ini harus melekat pada teks agama, yang perlu dicarikan pemaknaannya secara kontekstual. Benturan antara agama dan filsafat pernah didamaikan oleh Ibnu Rusyd, dalam tulisannya berjudul ”Fashl al-Maqal wa Taqrir ma Baina al-Syari’ah wa al-Hikmah min al-Ittisal”.
Bahkan Ibnu Rusyd menganjurkan penggunaan filsafat dalam memahami agama karena pendekatan ini akan sangat membantu dalam memahami agama. Rasionalitas inherent dalam makna teks, dan menjadi kebutuhan sejarah (historical necessity) saat ini.
Agama adalah untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Pengamalan kita dalam beragama, di samping sebagai bentuk penyembahan dan kepasrahan total kepada Tuhan (aslama, islam), juga diorientasikan untuk membebaskan manusia dari segala macam ketidakadilan, penindasan, dan kemiskinan. Agama adalah jalan bagi kemungkinan untuk meneguhkan kemanusiaan ditegakkan di muka bumi ini. Dan semuanya tergantung pada bagaimana manusia membumikan makna agama ke dalam wilayah praksis dengan berangkat dari rasionalisasi teks.
Membangun Dialog
Konfrontasi teks dengan humanisme perlu didialogkan. Mamadiou Dia dalam tulisannya ”Islam dan Humanisme”, yang dimuat dalam buku terbitan Paramadina, Islam Liberal (2001) suntingan Charles Kurzman, menyatakan bahwa untuk menemukan basis-basis Teologis Humanisme Islam, maka dibutuhkan konfontrasi dengan sumber-sumber yang dijadikan landasan bagi reformasi, untuk menemukan basis-basisnya yang memadukan nalar, masyarakat, dan sejarah.
Bagi Mamadiou, persoalannya terletak pada bagaimana memandang secara kreatif tentang Tuhan. Agama adalah kekuatan spiritual yang tinggi yang menggantikan suara hati manusia akan ”cita dunia” untuk Tuhan, sehingga perlunya elaborasi makna baru agama dengan perspektif menyertakan cita kemajuan, cita kemanusiaan, dan cita bumi. Kata Mamadiou, untuk mengelaborasikan pemaknaan seperti ini, maka perlu perangkat-perangkat konseptual yang menyertainya, sebagai bentuk dialog Islam dengan humanisme.
Sudah saatnya Islam dapat melakukan dialog dengan berbagai rujukan pengetahuan kontemporer --dari manapun-- agar diperoleh pemahaman Islam yang mampu membaca terhadap berbagai kompleksitas persoalan aktual-kekinian, seperti masalah kemanusiaan, keadilan, dan lain sebagainya. Langkahnya antara lain: Pertama, dengan barangkat dari gagasan pluralisme pemikiran kita melakukan dialektika wacana mengenai hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta, secara kreatif, aktif, dan dinamis. Beragama di samping berorientasi secara vertikal (untuk Tuhan), tapi juga tidak kalah pentingnya memproyeksikan keberagamaan kita untuk manusia dan kemanusiaan (antroposentris).
Kedua, perlu ada upaya secara massif melakukan rekonstruksi terhadap ilmu-ilmu keagamaan (‘ulum ad-dien), seperti ushul fiqh, ilmu hadits, dan sebagainya. Harus ada keterbukaan dalam menerima berbagai masukan (rujukan) dari perangkat-perangkat keilmuan kontemporer, seperti filsafat, hermeneutika, dekonstruksi, dan semantik. Oleh sebab itu, perangkat ijtihad perlu direkonstruksi menjadi lebih dinamis. Dan ketiga, perlu ada gerakan ”revitalisasi turats (tradisi)” --meminjam bahasanya Hassan Hanafi-- yaitu mendialogkan antara teks dan realitas menurut kerangka berpikir kekinian dan kedisinian.
Penulis adalah Peneliti The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia.
Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0310/15/opi01.html
Dimuat dalam Harian Sinar Harapan, 15 Oktober 2003.
Ide ”Islam Humanis” menjadi penting untuk didiskusikan kembali karena ”tamparan” hebat modernitas yang menggerus kepekaan kemanusiaan global. Dan juga disebabkan karena peran agama yang secara negatif telah disalahgunakan oleh penganutnya. Fenomena pengeboman dan aksi terorisme yang kian marak terjadi menambah rentetan derita kemanusiaan.
Wacana mengenai Islam dan humanisme menjadi penting untuk diperbincangkan kembali. Apakah Islam cenderung berlawanan dengan ajaran kemanusiaan? Bagaimana ada kemungkinan untuk membangun ruang dialog dalam upaya menghubungkan Islam dengan humanisme (ajaran kemanusiaan)? Upaya ini bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam agar lebih berwajah humanis dan berorientasi pada pemenuhan cita-cita kemanusiaan.
Humanisme Barat
Gerakan Renaisans (Pencerahan) yang muncul Pasca-Abad Pertengahan memberikan angin segar perubahan menuju pencerahan intelektualisme dan rasionalisme. Gereja dan agama yang telah menutup ruang kebebasan bagi manusia yang kemudian diprotes oleh Reformasi Protestan, melapangkan jalan sekularisasi antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Renaisans adalah era ”kebangkitan kembali” untuk menggali kebudayaan-kebudayaan Yunani dan Romawi, yang telah berabad-abad lamanya dikubur oleh masyarakat abad pertengahan di bawah kekuasaan gereja.
Pada masa inilah gerakan humanisme muncul. Warisan Yunani-Romawi yang dibangkitkan kembali adalah penghargaan atas dunia-sini, penghargaan atas martabat manusia, dan pengakuan atas kemampuan rasio. Gerakan humanisme mempercayai akan kemampuan manusia (sebagai ganti atas kemampuan adikodrati), hasrat intelektual, dan penghargaan atas disiplin intelektual. Pada masa abad pertengahan, segala hal pemikiran yang berbau rasio dan filosofis diharamkan, semua harus mengikuti doktrin agama (Kristiani).
Humanisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan pokok yang dimilikinya adalah untuk keselamatan dan kesempurnaan manusia (Ali Syari’ati,1989). Atau humanisme bisa juga diartikan sebagai paham pemikiran dan gerakan kultural yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai subyek yang bebas dan berdaulat dalam menentukan hidupnya (Sudarminta, 2001). Intinya, humanisme ingin meneguhkan kemampuan manusia secara bebas dan berdaulat untuk mengarungi hidupnya sendiri.
Dalam pandangan liberalisme Barat, tercapainya pengembangan potensi-potensi manusia bisa dilakukan dengan cara memberikan kebebasan pribadi dan kebebasan berpikir kepada manusia. Marxisme sebaliknya menyatakan bahwa kemanusiaan bisa ditegakkan apabila persamaan manusia yang tidak mengakui kebebasan-kebebasan tersebut, dan memasungnya ke dalam kepemimpinan diktator tunggal, yang dibantu oleh kelompok dan ideologi tunggal. Sebaliknya, eksistensialisme memberikan justifikasi filosofis bahwa manusia adalah makhluk yang berwujud dengan sendirinya di alam semesta. Yakni, makhluk yang dalam dirinya tidak terdapat bagian atau karakteristik tertentu yang datang dari Tuhan atau alam.
Humanisme yang terdapat pada ketiga aliran di atas berasal dari konsepsi Humanisme Yunani. Konsep ini berasal dari pertarungan antara langit dan bumi. Seluruh perbuatan dan kesadaran manusia dipimpin oleh kekuasaan yang zalim, yaitu para dewa sehingga manusia mencoba untuk membebaskan diri dari cengkeram kekuasaannya. Humanisme Yunani berusaha untuk mencapai jati diri manusia dengan segala kebenciannya kepada Tuhan dan pengingkaran atas kekuasaan-Nya. Ali Syari’ati memasukkan agama (termasuk Islam) sebagai salah satu madhab atau aliran humanisme.
John Avery, dalam dialognya dengan Hassan Askari yang terekam dalam buku Towards a Spiritual Humanism: A Muslim Humanist Dialogue (Meed: Seven Mirros,1991), mencatat bahwa kemunculan humanis agamis abad ke-20, seperti John Dewey, Roy Wood Sellars, dan sebagainya dari kubu Universitas Cambridge, menemukan unsur-unsur humanitarian dalam agama. Misalnya, ungkapan Yesus yang selalu mencintai manusia dengan doktrin kasih sayangnya, juga ajaran Islam yang menaruh perhatian terhadap aspek-aspek kemanusiaan. Kelompok humanis agamis berargumen bahwa agama dan kebudayaan manusia membantu atas kesadaran diri yang akan memeliharanya dari keterasingan hidup di dunia.Agama dan humanisme tidak selamanya berada pada ruang penuh pertentangan. Karena, ajaran agama yang dimaknai secara humanis dan rasional akan melapangkan citra positif bagi peran agama yang apresiatif dengan konteks kemanusiaan. Demikian halnya hubungan antara Islam dan humanisme. Ali Syari’ati memasukkan agama (termasuk Islam) sebagai salah satu madhab atau aliran humanisme.
Humanisme dalam Islam
Jika kita perhatikan sebenarnya Islam tidak bertentangan dengan humanisme. Tugas besar Islam, sejatinya adalah melakukan transformasi sosial dan budaya-budaya dengan nilai-nilai Islam. Kita mengenal trilogi ”iman-ilmu-amal” ; artinya iman berujung pada amal/aksi, atau tauhid itu harus diaktualisasikan dalam bentuk pembebasan manusia. Pusat keimanan Islam memang Tuhan, tetapi ujung aktualisasinya adalah manusia. Dalam penyataan Cak Nur (1995), pandangan hidup yang teosentris dapat dilihat dalam kegiatan keseharian yang antroposentris.
Dalam pandangan Kuntowijoyo (1991), Islam adalah sebuah humanisme, yaitu agama yang sangat mementingkan manusia sebagai tujuan sentral. Humanisme adalah nilai dasar Islam. Ia memberikan istilah dengan ”Humanisme Teosentris”, dengan pengertian ”Islam merupakan sebuah agama yang memusatkan dirinya pada keimanan Tuhan, tetapi yang mengarahkan perjuangannya untuk kemuliaan peradaban manusia”.
Islam sangat menjunjung tinggi rasionalisme. Untuk menghubungkan Islam dengan persoalan kemanusiaan dan humanisme maka teks keagamaan harus didekati secara rasional. Berbeda dengan Humanisme Teosentris, yang masih berangkat pada ajaran normatif agama --dengan pengandaian sudah final-- ”Humanisme Teistik”, sebagai istilah baru, memandang bahwa persoalannya terletak pada teks agama. Bagaimana sikap kita memperlakukan teks agar sesuai dengan konteks kekinian dan kemaslahatan (maslahah).
M. Abed Al-Jabiri (1991) menyodorkan dua model pembacaan terhadap teks keagamaan (tradisi) agar sesuai dengan konteks kekinian, yaitu ”Obyektivisme” (maudlu’iyyah) dan ”Rasionalitas” (ma’quliyah). Langkahnya, Pertama, bagaimana menjadikan tradisi lebih kontekstual dengan kekinian, tapi memisahkan terlebih dahulu dengan konteks yang ada agar didapati pemaknaan yang obyektif. Kedua, baru kemudian bagaimana memproyeksikan posisi obyektif itu dengan bagan rasionalitas yang relevan dengan masa kini.
Humanisme dalam Islam mengandung dua dimensi, yaitu ”rasionalitas” (rationality) dan ”pembebasan” (humanity). Dua dimensi ini harus melekat pada teks agama, yang perlu dicarikan pemaknaannya secara kontekstual. Benturan antara agama dan filsafat pernah didamaikan oleh Ibnu Rusyd, dalam tulisannya berjudul ”Fashl al-Maqal wa Taqrir ma Baina al-Syari’ah wa al-Hikmah min al-Ittisal”.
Bahkan Ibnu Rusyd menganjurkan penggunaan filsafat dalam memahami agama karena pendekatan ini akan sangat membantu dalam memahami agama. Rasionalitas inherent dalam makna teks, dan menjadi kebutuhan sejarah (historical necessity) saat ini.
Agama adalah untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Pengamalan kita dalam beragama, di samping sebagai bentuk penyembahan dan kepasrahan total kepada Tuhan (aslama, islam), juga diorientasikan untuk membebaskan manusia dari segala macam ketidakadilan, penindasan, dan kemiskinan. Agama adalah jalan bagi kemungkinan untuk meneguhkan kemanusiaan ditegakkan di muka bumi ini. Dan semuanya tergantung pada bagaimana manusia membumikan makna agama ke dalam wilayah praksis dengan berangkat dari rasionalisasi teks.
Membangun Dialog
Konfrontasi teks dengan humanisme perlu didialogkan. Mamadiou Dia dalam tulisannya ”Islam dan Humanisme”, yang dimuat dalam buku terbitan Paramadina, Islam Liberal (2001) suntingan Charles Kurzman, menyatakan bahwa untuk menemukan basis-basis Teologis Humanisme Islam, maka dibutuhkan konfontrasi dengan sumber-sumber yang dijadikan landasan bagi reformasi, untuk menemukan basis-basisnya yang memadukan nalar, masyarakat, dan sejarah.
Bagi Mamadiou, persoalannya terletak pada bagaimana memandang secara kreatif tentang Tuhan. Agama adalah kekuatan spiritual yang tinggi yang menggantikan suara hati manusia akan ”cita dunia” untuk Tuhan, sehingga perlunya elaborasi makna baru agama dengan perspektif menyertakan cita kemajuan, cita kemanusiaan, dan cita bumi. Kata Mamadiou, untuk mengelaborasikan pemaknaan seperti ini, maka perlu perangkat-perangkat konseptual yang menyertainya, sebagai bentuk dialog Islam dengan humanisme.
Sudah saatnya Islam dapat melakukan dialog dengan berbagai rujukan pengetahuan kontemporer --dari manapun-- agar diperoleh pemahaman Islam yang mampu membaca terhadap berbagai kompleksitas persoalan aktual-kekinian, seperti masalah kemanusiaan, keadilan, dan lain sebagainya. Langkahnya antara lain: Pertama, dengan barangkat dari gagasan pluralisme pemikiran kita melakukan dialektika wacana mengenai hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta, secara kreatif, aktif, dan dinamis. Beragama di samping berorientasi secara vertikal (untuk Tuhan), tapi juga tidak kalah pentingnya memproyeksikan keberagamaan kita untuk manusia dan kemanusiaan (antroposentris).
Kedua, perlu ada upaya secara massif melakukan rekonstruksi terhadap ilmu-ilmu keagamaan (‘ulum ad-dien), seperti ushul fiqh, ilmu hadits, dan sebagainya. Harus ada keterbukaan dalam menerima berbagai masukan (rujukan) dari perangkat-perangkat keilmuan kontemporer, seperti filsafat, hermeneutika, dekonstruksi, dan semantik. Oleh sebab itu, perangkat ijtihad perlu direkonstruksi menjadi lebih dinamis. Dan ketiga, perlu ada gerakan ”revitalisasi turats (tradisi)” --meminjam bahasanya Hassan Hanafi-- yaitu mendialogkan antara teks dan realitas menurut kerangka berpikir kekinian dan kedisinian.
Penulis adalah Peneliti The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia.
Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0310/15/opi01.html
Menyoroti Fenomena Radikalisme Agama
Oleh Happy Susanto
Dimuat dalam Website Jaringan Islam Liberal (JIL), 10/09/2003
Pengeboman di Hotel Marriot dan juga pengeboman sebelumnya mengindikasikan bahwa gerakan “radikalisme agama” menjadi sebuah kekuatan yang laten, muncul tiba-tiba dan berbahaya. Kekerasan atas nama agama menyebabkan pada situasi di mana agama kini sedang mengalami pengujian sejarah secara kritis. Bandul pendulum agama tergantung pada persepsi dan perilaku penganutnya yang akan mengarahkan pada dua sisi, yaitu “humanisasi” atau justru malah sebaliknya, “dehumanisasi”.
Fenomena kekerasan sudah sangat lama terjadi. Kekerasan sering dijadikan alat ampuh untuk memenuhi keinginan beberapa individu atau kelompok terhadap masalah yang begitu kompleks. Dan ternyata kekerasan juga menghinggapi pada agama-agama.
Di tengah memudarnya pesona modernitas, seperti yang pernah disampaikan Max Weber, ternyata pesona agama juga sedikit agak memudar. Sejak lama, kajian dalam pemikiran Islam bermuara pada perdebatan dalam menyoal hubungan antara tradisi (agama) dan modernitas (perubahan).
Bagi pihak yang cenderung menolak modernitas dan lebih mengukuhkan pada penancapan fungsi peran formal agama akan cenderung pada sikap “fundamentalisme”. Demikian hal sebaliknya. Jika pihak-pihak yang lebih menganggap modernitas sebagai satu-satunya realitas yang tak dapat ditampik dengan jalan menggeser peran agama, maka kecenderungan sikap yang muncul adalah “sekularisme”; memisahkan agama dari kehidupan duniawi dan memisahkan agama dari politik dan negara.
Dari ketegangan polarisasi kedua kubu di atas akan muncul sikap-sikap kekerasan. Dan kekerasan yang sering banyak muncul adalah dari kelompok fundamentalisme agama. Karena mereka sering disisihkan, dipinggirkan, dan ditindas oleh kekuatan sekuler yang bertengger di atas singgasana kekuasaan, maka tiada cara yang ampuh untuk digelar kecuali melawan dengan aksi kekerasan.
Genealogi Radikalisme
Terkadang kita sering menyamakan istilah “fundamentalisme” dan “radikalisme”. Padahal, keduanya berbeda walaupun berasal dari akar yang sama. Fundamentalisme (al-ushuliyah) lebih merupakan sebuah keyakinan untuk kembali pada fundamen-fundamen agama. Maknanya bisa positif atau negatif. Ekses negatif yang diakibatkan dari pandangan yang fundamentalis ini adalah sikap kekerasan (radikalisme ekstrem).
Penyandingan kekerasan dengan radikalisme disebabkan karena gejala dalam realitas sosial yang sering nampak. Kelompok radikal sering menggunakan cara-cara kekerasan dalam memenuhi keinginan atau kepentingan mereka. Tapi, kelompok radikal tidak identik dengan kekerasan. Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan radikalisme agama adalah “sikap keagamaan yang kaku dan juga sekaligus mengandung kekerasan dalam tindakan”. Penyebutan ini dimaksudkan untuk mempermudah kategorisasi.
Geneaogi radikalisme agama muncul karena beberapa sebab. Dalam kasus Islam, misalnya, Hassan Hanafi (2001) menyebut --paling tidak-- ada dua sebab kemunculan aksi kekerasan dalam Islam kontemporer. Pertama, karena tekanan rezim politik yang berkuasa. Kelompok Islam terentu tidak mendapat hak kebebasan berpendapat. Kedua, kegagalan-kegagalan ideologi sekuler rezim yang berkuasa, ehingga kehadiran fundamentalisme atau radikalisme agama dianggap sebagai alternatif ideologis satu-satunya pilihan yang nyata bagi umat Islam.
Kekerasan dalam agama muncul karena ketiadaan kemampuan dalam menghadapi modernitas dan perubahan. Perlu digarisbawahi, fundamentalisme merupakan spirit gerakan dalam radikalisme agama. Pembacaan atas fundamentalisme pernah digarap oleh Martin E. Marty dan R. Scott Appleby dalam Fundamentalisms Observed (Chicago dan London,1991). Mereka menyatakan bahwa fundamentalisme-fundamentalisme itu merupakan mekanisme pertahanan yang muncul sebagai reaksi atas krisis yang mengancam. Yaitu krisis keadaan yang akan menentukan eksistensi mereka. Karen Armstrong (2000) juga menyatakan bahwa gerakan fundamentalisme yang berkembang pada masa kini mempunyai hubungan erat dengan modernitas.
Karena gerakan radikalisme itu muncul sebagai respon atas modernitas maka kita sebaiknya melihat hubungan antara tradisi dan modernitas secara obyektif. Dalam tubuh modernitas juga mengandung banyak ekses negatif. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pengaruh modernitas juga memberikan implikasi kerusakan bagi eksistensi kemanusiaan. Modernitas perlu diantisipasi pula. Tapi, antisipasi yang dilakukan tidak menyebabkan “totalitas” penolakan atas dasar agama. Modernitas adalah sebuah fase sejarah yang mengelilingi kehidupan manusia, di mana terdapat sisi positif dan juga negatif.
Solusi atas Kekerasan
Kekerasan bukanlah merupakan sebuah tawaran yang bijak untuk menyikapi polarisasi dunia akibat tamparan hebat modernitas. Islam memiliki banyak kerangka pemikiran untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi. Hanya saja, eksplorasi atas makna-makna perdamaian dalam Islam telah dicemari oleh beberapa perilaku kekerasan oleh gerakan radikal. Tugas kaum agamawan adalah bagaimana menawarkan solusi atas kekerasan ini agar ada pernyataan bahwa kekerasan bukanlah ajaran Islam.
Fakta beberapa oknum pelaku pengeboman atau terorisme yang dilakukan oleh kelompok agama (Islam) memang bisa saja dibenarkan bahwa itu dilakukan oleh beberapa kelompok Islam radikal. Tapi, apakah penampilan Islam pasti seperti itu? Tidak. Apa yang dilakukan oleh gerakan Islam radikal sudah mengandung kompleksitas kondisional. Artinya, dengan tameng agama, apa yang mereka lakukan juga merupakan penyertaan pada sisi politis, ideologis, dan kepentingan non-agama yang melingkupi aksi mereka. Jadi, itu bukan an sich karena sisi penafsiran yang merupakan hasil pemaknaan agama yang sempit saja.
Dengan meminjam analisis Michael Faucoult, apa yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal sudah menggiring agama dalam hubungannya antara pengetahuan dan kekuasaan (power and knowledge). Pengetahuan yang ingin diwacanakan oleh kelompok Islam radikal adalah bahwa hukum Tuhan (ahkamullah) harus diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Dalam lokus politik, biasanya wacana yang digelar yaitu bentuk penyatuan ad-dien wad-daulah (agama dan negara). Tapi, wacana (pengetahuan) agama itu diperkuat dengan perangkat kekuasaan. Sehingga, gerakan yang mereka lakukan sudah sangat mengandung unsur ideologis. Ekses negatif karena tindak kekerasan menyebabkan agama menjadi berwajah buruk. Untuk itulah kaitan agama dan kekuasaan harus dipisahkan.
Karena kekerasan itu akibat dari modernitas, maka Peter L. Berger (2003) menawarkan dua strategi untuk merespon modernitas dan sekularisasi ini, yaitu “revolusi agama” (religious revolution) dan “subkultur agama” (religion subcultures). Yang pertama adalah bagaimana kaum agamawan mampu merubah masyarakat secara keseluruhan dan menghadirkan model agama yang modern. Dan yang kedua adalah bagaimana upaya kita untuk mencegah pengaruh-pengaruh luar agar tidak mudah masuk ke dalam agama.
Gerakan Islam radikal muncul karena pemahaman agama yang cenderung tekstualis, sempit, dan hitam-putih. Pemahaman seperti ini akan dengan mudah menggiring sang pembaca pada sikap keberagamaan yang kaku. Pembacaan agama tidak bisa terlepas dari konteks historisnya. Pemahaman agama sangat dimanis. Untuk itulah, pembacaan yang terbuka akan menghindarkan kita dari sikap-sikap yang berbau kekerasan.
Solusi yang bisa ditawarkan dalam menyikapi fenomena radikalisme agama antara lain: pertama, menampilkan Islam sebagai ajaran universal yang memberikan arahan bagi terciptanya perdamaian di muka bumi. Kedua, perlu ada upaya penggalangan aksi untuk menolak sikap kekerasan dan terorisme. Aksi ini melibatkan seluruh kelompok-kelompok dalam agama-agama yang tidak menghendaki hal demikian. Terorisme dan kekerasan adalah bentuk pelecehan atas nama agama dan kemanusiaan.
Ketiga, sudah saatnya kita menumbuhkan karakter keberagamaan yang moderat. Memahami dinamika kehidupan ini secara terbuka dengan menerima pluralitas pemikiran “yang lain” (the other), yang ada di luar kelompoknya. Keberagaman yang moderat akan melunturkan polarisasi antara fundamentalisme dan sekularisme dalam menyikapi modernitas dan perubahan. Islam yang di tengah-tengah (ummatan wasathan) akan membentuk karakter Islam yang demokratis, terbuka, dan juga rasional.
Islam hadir juga untuk memenuhi panggilan kemanusiaan dan perdamaian. Adalah tugas kita semua untuk memberikan citra positif bagi Islam yang memang berwajah humanis dan anti-kekerasan ini. Hanya sejarahlah yang akan membuktikan apakah agama mampu hadir seperti yang dicita-citakannya. Wallahu A’lam bish-Shawab.
Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=412
Dimuat dalam Website Jaringan Islam Liberal (JIL), 10/09/2003
Pengeboman di Hotel Marriot dan juga pengeboman sebelumnya mengindikasikan bahwa gerakan “radikalisme agama” menjadi sebuah kekuatan yang laten, muncul tiba-tiba dan berbahaya. Kekerasan atas nama agama menyebabkan pada situasi di mana agama kini sedang mengalami pengujian sejarah secara kritis. Bandul pendulum agama tergantung pada persepsi dan perilaku penganutnya yang akan mengarahkan pada dua sisi, yaitu “humanisasi” atau justru malah sebaliknya, “dehumanisasi”.
Fenomena kekerasan sudah sangat lama terjadi. Kekerasan sering dijadikan alat ampuh untuk memenuhi keinginan beberapa individu atau kelompok terhadap masalah yang begitu kompleks. Dan ternyata kekerasan juga menghinggapi pada agama-agama.
Di tengah memudarnya pesona modernitas, seperti yang pernah disampaikan Max Weber, ternyata pesona agama juga sedikit agak memudar. Sejak lama, kajian dalam pemikiran Islam bermuara pada perdebatan dalam menyoal hubungan antara tradisi (agama) dan modernitas (perubahan).
Bagi pihak yang cenderung menolak modernitas dan lebih mengukuhkan pada penancapan fungsi peran formal agama akan cenderung pada sikap “fundamentalisme”. Demikian hal sebaliknya. Jika pihak-pihak yang lebih menganggap modernitas sebagai satu-satunya realitas yang tak dapat ditampik dengan jalan menggeser peran agama, maka kecenderungan sikap yang muncul adalah “sekularisme”; memisahkan agama dari kehidupan duniawi dan memisahkan agama dari politik dan negara.
Dari ketegangan polarisasi kedua kubu di atas akan muncul sikap-sikap kekerasan. Dan kekerasan yang sering banyak muncul adalah dari kelompok fundamentalisme agama. Karena mereka sering disisihkan, dipinggirkan, dan ditindas oleh kekuatan sekuler yang bertengger di atas singgasana kekuasaan, maka tiada cara yang ampuh untuk digelar kecuali melawan dengan aksi kekerasan.
Genealogi Radikalisme
Terkadang kita sering menyamakan istilah “fundamentalisme” dan “radikalisme”. Padahal, keduanya berbeda walaupun berasal dari akar yang sama. Fundamentalisme (al-ushuliyah) lebih merupakan sebuah keyakinan untuk kembali pada fundamen-fundamen agama. Maknanya bisa positif atau negatif. Ekses negatif yang diakibatkan dari pandangan yang fundamentalis ini adalah sikap kekerasan (radikalisme ekstrem).
Penyandingan kekerasan dengan radikalisme disebabkan karena gejala dalam realitas sosial yang sering nampak. Kelompok radikal sering menggunakan cara-cara kekerasan dalam memenuhi keinginan atau kepentingan mereka. Tapi, kelompok radikal tidak identik dengan kekerasan. Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan radikalisme agama adalah “sikap keagamaan yang kaku dan juga sekaligus mengandung kekerasan dalam tindakan”. Penyebutan ini dimaksudkan untuk mempermudah kategorisasi.
Geneaogi radikalisme agama muncul karena beberapa sebab. Dalam kasus Islam, misalnya, Hassan Hanafi (2001) menyebut --paling tidak-- ada dua sebab kemunculan aksi kekerasan dalam Islam kontemporer. Pertama, karena tekanan rezim politik yang berkuasa. Kelompok Islam terentu tidak mendapat hak kebebasan berpendapat. Kedua, kegagalan-kegagalan ideologi sekuler rezim yang berkuasa, ehingga kehadiran fundamentalisme atau radikalisme agama dianggap sebagai alternatif ideologis satu-satunya pilihan yang nyata bagi umat Islam.
Kekerasan dalam agama muncul karena ketiadaan kemampuan dalam menghadapi modernitas dan perubahan. Perlu digarisbawahi, fundamentalisme merupakan spirit gerakan dalam radikalisme agama. Pembacaan atas fundamentalisme pernah digarap oleh Martin E. Marty dan R. Scott Appleby dalam Fundamentalisms Observed (Chicago dan London,1991). Mereka menyatakan bahwa fundamentalisme-fundamentalisme itu merupakan mekanisme pertahanan yang muncul sebagai reaksi atas krisis yang mengancam. Yaitu krisis keadaan yang akan menentukan eksistensi mereka. Karen Armstrong (2000) juga menyatakan bahwa gerakan fundamentalisme yang berkembang pada masa kini mempunyai hubungan erat dengan modernitas.
Karena gerakan radikalisme itu muncul sebagai respon atas modernitas maka kita sebaiknya melihat hubungan antara tradisi dan modernitas secara obyektif. Dalam tubuh modernitas juga mengandung banyak ekses negatif. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pengaruh modernitas juga memberikan implikasi kerusakan bagi eksistensi kemanusiaan. Modernitas perlu diantisipasi pula. Tapi, antisipasi yang dilakukan tidak menyebabkan “totalitas” penolakan atas dasar agama. Modernitas adalah sebuah fase sejarah yang mengelilingi kehidupan manusia, di mana terdapat sisi positif dan juga negatif.
Solusi atas Kekerasan
Kekerasan bukanlah merupakan sebuah tawaran yang bijak untuk menyikapi polarisasi dunia akibat tamparan hebat modernitas. Islam memiliki banyak kerangka pemikiran untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi. Hanya saja, eksplorasi atas makna-makna perdamaian dalam Islam telah dicemari oleh beberapa perilaku kekerasan oleh gerakan radikal. Tugas kaum agamawan adalah bagaimana menawarkan solusi atas kekerasan ini agar ada pernyataan bahwa kekerasan bukanlah ajaran Islam.
Fakta beberapa oknum pelaku pengeboman atau terorisme yang dilakukan oleh kelompok agama (Islam) memang bisa saja dibenarkan bahwa itu dilakukan oleh beberapa kelompok Islam radikal. Tapi, apakah penampilan Islam pasti seperti itu? Tidak. Apa yang dilakukan oleh gerakan Islam radikal sudah mengandung kompleksitas kondisional. Artinya, dengan tameng agama, apa yang mereka lakukan juga merupakan penyertaan pada sisi politis, ideologis, dan kepentingan non-agama yang melingkupi aksi mereka. Jadi, itu bukan an sich karena sisi penafsiran yang merupakan hasil pemaknaan agama yang sempit saja.
Dengan meminjam analisis Michael Faucoult, apa yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal sudah menggiring agama dalam hubungannya antara pengetahuan dan kekuasaan (power and knowledge). Pengetahuan yang ingin diwacanakan oleh kelompok Islam radikal adalah bahwa hukum Tuhan (ahkamullah) harus diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Dalam lokus politik, biasanya wacana yang digelar yaitu bentuk penyatuan ad-dien wad-daulah (agama dan negara). Tapi, wacana (pengetahuan) agama itu diperkuat dengan perangkat kekuasaan. Sehingga, gerakan yang mereka lakukan sudah sangat mengandung unsur ideologis. Ekses negatif karena tindak kekerasan menyebabkan agama menjadi berwajah buruk. Untuk itulah kaitan agama dan kekuasaan harus dipisahkan.
Karena kekerasan itu akibat dari modernitas, maka Peter L. Berger (2003) menawarkan dua strategi untuk merespon modernitas dan sekularisasi ini, yaitu “revolusi agama” (religious revolution) dan “subkultur agama” (religion subcultures). Yang pertama adalah bagaimana kaum agamawan mampu merubah masyarakat secara keseluruhan dan menghadirkan model agama yang modern. Dan yang kedua adalah bagaimana upaya kita untuk mencegah pengaruh-pengaruh luar agar tidak mudah masuk ke dalam agama.
Gerakan Islam radikal muncul karena pemahaman agama yang cenderung tekstualis, sempit, dan hitam-putih. Pemahaman seperti ini akan dengan mudah menggiring sang pembaca pada sikap keberagamaan yang kaku. Pembacaan agama tidak bisa terlepas dari konteks historisnya. Pemahaman agama sangat dimanis. Untuk itulah, pembacaan yang terbuka akan menghindarkan kita dari sikap-sikap yang berbau kekerasan.
Solusi yang bisa ditawarkan dalam menyikapi fenomena radikalisme agama antara lain: pertama, menampilkan Islam sebagai ajaran universal yang memberikan arahan bagi terciptanya perdamaian di muka bumi. Kedua, perlu ada upaya penggalangan aksi untuk menolak sikap kekerasan dan terorisme. Aksi ini melibatkan seluruh kelompok-kelompok dalam agama-agama yang tidak menghendaki hal demikian. Terorisme dan kekerasan adalah bentuk pelecehan atas nama agama dan kemanusiaan.
Ketiga, sudah saatnya kita menumbuhkan karakter keberagamaan yang moderat. Memahami dinamika kehidupan ini secara terbuka dengan menerima pluralitas pemikiran “yang lain” (the other), yang ada di luar kelompoknya. Keberagaman yang moderat akan melunturkan polarisasi antara fundamentalisme dan sekularisme dalam menyikapi modernitas dan perubahan. Islam yang di tengah-tengah (ummatan wasathan) akan membentuk karakter Islam yang demokratis, terbuka, dan juga rasional.
Islam hadir juga untuk memenuhi panggilan kemanusiaan dan perdamaian. Adalah tugas kita semua untuk memberikan citra positif bagi Islam yang memang berwajah humanis dan anti-kekerasan ini. Hanya sejarahlah yang akan membuktikan apakah agama mampu hadir seperti yang dicita-citakannya. Wallahu A’lam bish-Shawab.
Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=412
Subscribe to:
Posts (Atom)